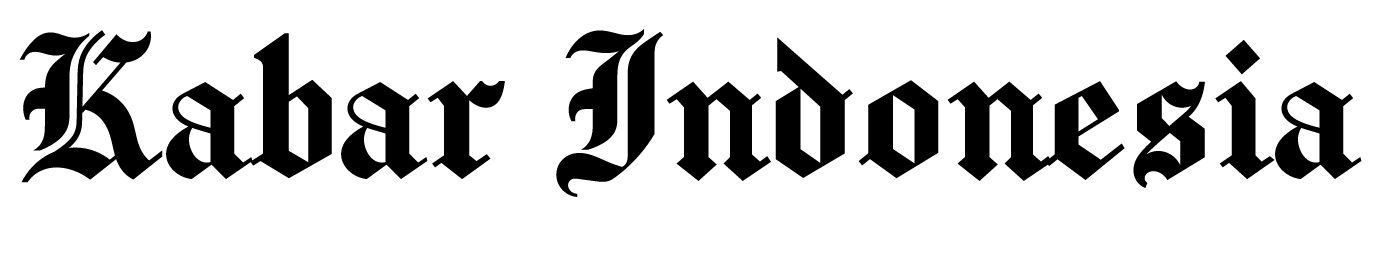Pengantar
Pemilu 2024 telah mencatatkan salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah demokrasi pasca-reformasi Indonesia: majunya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden. Bagi sebagian, ini adalah prestasi politik anak muda. Namun bagi sebagian besar lainnya, ini adalah simbol kerapuhan etika politik dan pembusukan rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.
Kepantasan Bukan Sekadar Legalitas
Majunya Gibran memang telah mendapat legitimasi hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Namun di titik inilah polemik bermula. Putusan itu tidak datang dalam ruang hampa: diketuai oleh Anwar Usman, ipar Presiden Jokowi, lalu berujung pada sanksi etik berat oleh Majelis Kehormatan MK. Praktik semacam ini mencederai kepantasan sosial yang tumbuh dari prinsip keadilan dan keterbukaan.
Sejarawan dan budayawan JJ Rizal menyebut langkah tersebut sebagai “pelecehan terhadap nalar demokrasi dan pengkhianatan terhadap semangat reformasi.” Ia menegaskan bahwa “politik tidak hanya soal sah atau tidak, tetapi juga layak atau tidak.”
Reaksi Masyarakat: Dari Apatis hingga Marah
Survei Litbang Kompas yang dirilis November 2023 menunjukkan bahwa 68% responden menyatakan “tidak setuju jika anak presiden maju sebagai cawapres saat ayahnya masih menjabat.” Angka ini menunjukkan bahwa secara sosial, publik belum siap menerima politik dinasti sebagai norma baru.
Lebih jauh lagi, gerakan mahasiswa, tokoh-tokoh sipil, bahkan beberapa akademisi dari UGM—almamater Jokowi dan Gibran—ikut bersuara lantang. Dalam petisi terbuka, mereka menulis: “Kami menolak praktik pelemahan demokrasi yang ditandai oleh upaya penguasaan kekuasaan secara terstruktur dan sistematis oleh keluarga penguasa.”
Efek Domino terhadap Rasa Sosial
Di ruang-ruang diskusi publik, terutama di kalangan kelas menengah urban, muncul satu kata yang terus berulang: “muak.” Muak dengan pencitraan. Muak dengan dinasti. Muak dengan demokrasi yang dipermainkan.
Sosiolog Imam Prasodjo menyebut ini sebagai “keterbelahan rasa sosial.” Menurutnya, “masyarakat yang awalnya mendukung Jokowi karena dianggap dari rakyat biasa, kini merasa dikhianati ketika kekuasaan itu justru diwariskan kepada keluarga.” Artinya, luka yang tercipta bukan sekadar soal siapa yang maju, tetapi siapa yang dilangkahi dan bagaimana proses itu terjadi.
Preseden Berbahaya: Normalisasi Politik Kekerabatan
Jika keputusan ini diterima begitu saja oleh masyarakat dan elite politik, maka Indonesia sedang membuka gerbang lebar bagi normalisasi politik dinasti. Demokrasi berubah menjadi oligarki berkedok pemilu. Meritokrasi dikubur, dan rasa keadilan masyarakat terkikis.
Pakar tata negara Bivitri Susanti menegaskan: “Ini bukan lagi soal Gibran semata, tapi soal arsitektur sistem demokrasi kita. Kalau hari ini aturan bisa diubah untuk satu orang, besok siapa yang akan jadi pengecualian berikutnya?”
Penutup: Demokrasi Tak Cukup Hanya Legal, Ia Harus Layak
Indonesia layak dipimpin oleh anak muda, oleh pemimpin segar yang lahir dari proses jujur dan adil. Namun jalan cepat yang dilalui Gibran, dengan karpet merah dari kekuasaan ayahnya, telah meninggalkan luka sosial yang dalam. Ini bukan tentang kompetensi, tapi tentang etika. Bukan tentang hukum, tapi tentang kepantasan.
Jika demokrasi hanya diukur dari ketaatan pada prosedur legal formal, maka kita lupa bahwa demokrasi lahir dari semangat keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan kepada rakyat. Dan di titik ini, publik berhak bertanya: benarkah Gibran maju karena rakyat, atau karena darah?
Oleh : M.A. Rahman
Catatan Redaksi:
Tulisan ini adalah opini pribadi penulis. Redaksi terbuka untuk publikasi pandangan dari semua pihak sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan diskursus publik yang sehat.